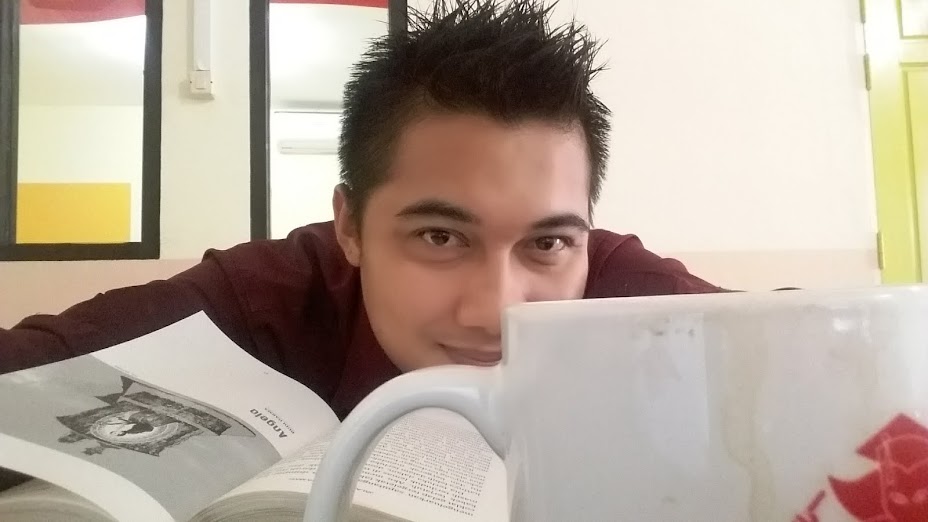Disinilah aku sekarang, di sebuah desa yang sejuk di kaki Gunung Merapi. Desa Paraksari. Bukan, ini bukan desaku. Aku sekedar berkunjung saja ke rumah sahabat terbaikku saat masih kuliah dulu. Lukman. Sudah lima tahun lamanya kami berpisah setelah lepas masa perkuliahan dulu. Kami bertemu lagi secara tak sengaja. Beberapa minggu yang lalu, aku diundang oleh Dandi, sahabat kami juga. Kapan hari itu Dandi me-launching buku pertamanya. Disinilah aku bertemu dengan Lukman. Segera saja kami bertiga terlibat pembicaraan yang sangat akrab dan hangat.
“Gila! Sastrawan Jakarta diundang juga? Waaaah, bisa minder aku ini.”
Aku tersenyum. Itulah komentar Lukman pertama kali saat dia melihatku berjalan beriringan bersama Dandi. Acara belum dimulai.
“Sastrawan? Hei, kau sudah menerbitkan buku. Dandi akan me-launching bukunya sebentar lagi. Lah, aku? Orang yang kau sebut sastrawan ini belum punya karya apa-apa. Sebenarnya siapa sih yang pantas mendapat gelar sastrawan?” kami bertiga terbahak, saling berpelukan setelahnya. Kabar terbaru segera meluncur dari bibir kami masing-masing.
Seusai acara, Lukman menawarkan singgah ke rumahnya. Aku menolak. Tentu saja aku punya alasan. Lukman juga bisa memahaminya. Lima tahun sudah kami meninggalkan bangku kuliah. Tentu saja kami punya kesibukan sendiri. Kami rasa, ini memang sudah menjadi keharusan. Bukan harus sibuk, tapi harus menerapkan ilmu yang kami dapat selama kuliah dulu.
“Kapan-kapan kalau kau punya waktu libur yang sedikit panjang, mampirlah ke gubukku. Aku senantiasa menunggu kunjunganmu, Lang.” Lukman menuliskan alamat rumahnya di kertas kecil. Segera diangsurkannya kertas itu ke aku begitu dia selesai menulis. Aku menerimanya dengan senang sambil dalam hati aku berjanji jika kelak ada waktu luang, aku akan berkunjung. Secepatnya.
***
Disinilah aku sekarang, di sebuah desa yang sejuk di kaki Gunung Merapi. Desa Paraksari. Aku menggunakan penerbangan pertama dari Jakarta. Sampai di Jogja, segera saja aku meluncur ke Kecamatan Pakem, alamat rumah Lukman yang dia tuliskan dulu, sebelum kami berpisah. Lukman bilang, rumahnya tidaklah begitu jauh dari Jogja. Hanya sekitar tujuh belas kilometer saja.
Bus yang aku tumpangi melaju tenang. Aku menemukan kedamaian disini, bahkan di dalam bus sekalipun. Sepanjang perjalanan, mataku tak lepas dari pemandangan yang tersaji dengan indah dan alami. Banyak sekali rumah penduduk yang kulihat sepi. Aku jadi ingat cerita Lukman dulu, sewaktu kami masih kuliah. Setiap malam Lukman selalu bercerita tentang desanya yang menyenangkan. Itu katanya.
“Kamu tau, Lang, desaku sepi. Sangat sepi malah. Tapi karena sepi itulah aku jadi senang mudik.” Lukman mulai bercerita. Aku mendengarkan dengan seksama sambil mencoba untuk terlelap.
“Lah, kok bisa gitu?”
“Apanya?”
“Ya itu tadi, sepi, tapi kamu malah suka.”
“Oh,” Lukman membenarkan letak bantalnya, “tentu saja aku suka. Kamu tau sendiri kan, gimana ramainya disini. Bising. Macet. Gerah. Kalau aku mudik, terus yang kutemui di desaku sama seperti yang terjadi di sini, mendingan aku gak usah mudik kan, Lang?”
Aku mulai mengerti dengan alur pikirannya. “Terus, kok bisa sepi gitu, orang-orangnya pada kemana?”
“Banyak yang merantau, Lang. terutama bapak-bapak dan remaja. Kalau ibu-ibu biasanya bekerja sebagai pemanen buah salak di beberapa perkebunan milik orang kaya.”
“Salak?” aku antusias. Segera saja kepalaku miring dan mencoba mencari kepastian atas cerita Lukman barusan. “Di desamu banyak salak?”
“Iya, banyak.”
“Waaaaah, mantap.”
“Kamu suka salak, Lang?”
“Gak.” Jawabku sekenanya. Kalau sudah begini, bantal yang persis berada di bawah kepala Lukman segera saja pindah ke mukaku.
Aku tersenyum. Semuanya melintas dikepalaku begitu saja. Kenangan itu terasa begitu indah.
Laju bis mulai melambat.
Tak sulit mencari tukang ojek disini. Kutunjukkan alamat yang tertera di kertas kumal pemberian Lukman tempo hari kepada salah satu tukang ojek yang aku temui. Setelahnya kami tawar menawar harga. Motor segera melaju perlahan setelah ada kesepakatan. Dan, segera saja dadaku bergetar hebat. Aku akan bertemu Lukman. Tidak, bukan hanya Lukman. Tapi aku akan bertemu dengan keluarganya. Anak dan istrinya.
Ojek berhenti. Persis di depan rumah mungil yang pekarangannya sangat luas. Aku takjub. Semilir yang dikirim oleh beberapa batang Akasia di tepi jalan segera menyambutku. Aku mematung. Masih takjub. Pandanganku mulai beredar liar. Dua buah taman kecil ditata begitu rapi. Bunga warna-warni melambai dengan lentik. Aroma yang begitu wangi segera menyergap memenuhi rongga hidung. Segar sekali. Setapak jalan kecil membelah persis ditengah-tengah taman. Jalan ini menuju beranda rumah yang mungil dan asri tadi. Kebahagiaan begitu terasa di rumah ini. Sejenak aku hanya bisa diam. Dadaku masih belum berhenti bergetar.
Pintu terbuka. Ojek sudah menghilang sejak tadi.
“Elang?”
Suara itu. Aku mendengarnya lagi. Aku tak kuasa untuk melangkah. Bahkan untuk sekedar membalas keterkejutannya sekalipun.
“Elang? Oh, masuklah. Ayo.”
Suara itu masih menggetarkan sebuah keterkejutan. Aku juga. Jujur, aku juga terkejut. Tentu saja beda. Suara itu terkejut tentu karena sama sekali tidak menyangka bahwa aku akan benar-benar berkunjung. Sementara aku? Aku terkejut karena, ah, bodohnya aku. Aku hanya terkejut lantaran kulihat perempuan yang berdiri di ambang pintu itu masih seperti dulu. Cantik.
Pelan, aku melangkah mendekati pintu. Segera aku disuguhi oleh paras bingung seorang perempuan yang tak tau harus memulai pembicaraan dari mana. Aku mulai mencoba meredakan detak jantungku yang masih saja menghantam dada. Kupandang lekat-lekat wajahnya, perempuan itu. Dia tertunduk. Niatku untuk berinisiatif memulai percakapan gagal.
“Duduklah, Lang. sebentar kuambilkan minum.”
Aku menerima tawarannya. Sebenarnya aku tidak merasa letih atau apalah namanya. Aku duduk karena ingin menenangkan diriku sendiri. Detak jantungku sendiri.
Perempuan itu segera kembali. Kuamati lakunya lekat-lekat. Manis sekali. Bahkan caranya menyuguhkan minum sekalipun.
“Mana Lukman, In?” aku mencoba mencairkan ketegangan.
“Biasalah, masih mengajar. Sebentar lagi juga pulang.” Indriana, perempuan dihadapanku ini, tersenyum. Aku benci. Bukan kepada senyumnya, tapi kepada gemuruh yang sekali lagi menghantam dadaku dengan hebat.
“Oiya, kamu apa kabar? Sejak menikah dengan Lukman, kamu seperti tenggelam, hilang ditelan bumi. Tak pernah lagi kubaca tulisanmu di koran lokal. Berhenti jadi penulis?”
Lagi, kulihat dia tersenyum. “Aku ya seperti yang kamu lihat sekarang ini. Ibu rumah tangga yang hanya sesekali saja merasa sibuk mengurusi taman kecil itu. Selebihnya, tak banyak yang aku lakukan. Menulis tak pernah aku tinggalkan. Aku suka bunga. Aku juga suka menulis. Hanya saja, tulisanku sekarang statusnya sebagai koleksi pribadi saja.”
Aku merasakan, ketegangan sudahpun mencair. Indriana segera saja menjelma sebagai gadis delapan belas tahun saat pertama kali kukenal dulu. Hangat. Ramah. Berbincang dengannya selalu saja membuatku kesulitan dalam satu hal: mengakhirinya.
Aku sendiri mulai bisa mengontrol detak jantungku. Semuanya akan baik-baik saja. Perbincangan ini sendiri mulai terasa mengalir apa adanya. Hangat seperti dulu. Kami tertawa bersama. Membicarakan kenangan-kenangan saat di bangku kuliah dulu. Semuanya hadir. Datang kembali tanpa bisa dicegah. Menyeruak memenuhi ruang dan waktu saat ini. Sebuah dimensi yang telah kami tinggalkan beberapa tahun lamanya. Kami paksa, kami seret untuk hadir kembali dan setelahnya kami tertawa. Menertawakan segala tingkah yang terkadang terasa begitu bodoh.
Sampai akhirnya kami dikejutkan oleh teriakan Lukman.
“ELAAAANG???”
Aku benar-benar terkejut. Lukman menghambur, memelukku dengan erat. Tawanya nyaring. Sungguh terasa bahwa dia bahagia. Tidak dibuat-buat. Matanya bulat membesar mengamatiku dari ujung rambut sampai ujung kaki. Diguncangkannya pundakku beberapa kali. Lukman tertawa lagi.
“Kau datang juga, jagoan. Ah, aku benar-benar senang hari ini. Kau benar-benar menginjakkan kakimu di gubukku yang renta ini. Selamat datang sahabatku Elang. Mari, kita ngopi dulu sambil menikmati lezatnya jadah tempe buatan istriku.”
Itulah Lukman. Seorang sahabat yang sampai saat ini belum pernah mengecewakanku sekalipun. Aku begitu bahagia dengan sambutannya ini.
“Kau tidak berubah.” aku memulai pembicaraan sesaat setelah Indri kembali. Sepiring jadah tempe terhidang dihadapan kami. “Kau masih saja suka berteriak kalau sedang gembira. Persis seperti dulu.”
Lukman tertawa. Indri juga. Tapi aku tidak berani menatapnya. Bibir yang tertawa itu. Bibir Indri.
“Jadi, apa sekarang kau sudah berubah?”
Aku mengangkat bahu. “Kau yang menilai, bukan aku yang mengaku.”
Lukman tertawa lagi. “Ternyata kau juga masih seperti yang dulu, Kawan. Kau suka berdiplomatis setiap menjawab pertanyaan. Aku suka itu.”
Aku mencomot sepotong jadah tempe. Mengunyahnya perlahan. Nikmat sekali. Lukman juga melakukan hal yang sama. Mencomot sepotong jadah tempe. Juga mengunyahnya perlahan. Kami tertawa menyadari ini.
“Kenapa kalian tertawa? Apa ada yang aneh?” Indri yang bertanya.
Aku memandang ke arah Lukman, memintanya untuk menjelaskan sebab kami tertawa barusan. Lukman sangat paham dengan isyaratku ini.
“Kami punya banyak kesamaan, In. banyak sekali. Mulai dari kebiasaan tertawa, cara makan yang sama, kesukaan makanan yang sama, bahkan dulu sewaktu kuliah, kami mencintai gadis yang bernama sama. Indriana. Bedanya, Elang gagal mendapatkan gadisnya.”
Aku tertawa membenarkan. Segera kutelan potong jadah tempe terakhir. Seketika rasanya menjadi tawar.
“Masih kau simpan foto gadismu itu, Lang?”
Aku tersenyum, “Tentu saja masih.” kuambil dompet di saku celana, kukeluarkan selembar foto yang sudah mulai kusut. “Ini. Cantik kan?”
Lukman menerima foto yang kuangsurkan. “Lihat foto ini, In,” Indri mendekat. “Cantik kan? Itulah salah satu kesamaan kami. Selera kami tinggi kalau menyangkut urusan gadis.”
Kusimpan kembali foto yang diangsurkan Lukman. Sejenak kulihat wajah Indri. Ekspresinya datar. Aku yakin dia tak hendak mengatakan apa-apa. Tentang gadis dalam foto itu tentu saja.
Sepi.
Sekali lagi aku berusaha menyeret sepotong kisah beberapa tahun yang lalu. Aku ingat waktu itu Lukman kaget setelah mendengar aku menyebutkan nama gadis yang ingin aku jadikan pacar. Dia bilang, nama yang aku sebutkan barusan sama persis dengan nama gadis yang juga ingin dia jadikan pacar. Akhirnya kami sepakat untuk saling menunjukkan foto gadis kami masing-masing. Aku memintanya menunjukkan foto gadisnya lebih dulu.
“Bagaimana? Cantik bukan?”
Aku tersenyum ketika itu. Aku suka dengan pilihannya. Gadis itu cantik sekali.
“Sekarang, tunjukkan foto gadis idamanmu.”
Aku mengeluarkan selembar foto. Kuserahkan ke Lukman. “Cantik gak?” kulihat Lukman berdecak beberapa kali.
“Cantik sekali, Lang. kamu pintar memilih calon.”
Kami tertawa. Waktu itu kami berjanji akan memperjuangkan cinta kami. Tentu saja seharusnya begitu.
Aku tersenyum. Tiba-tiba Lukman menepuk pundakku. Sepotong kenangan yang baru saja hinggap tadi seketika terbang.
“Menginaplah disini barang beberapa hari. Kita bercerita sepuas-puasnya. Nanti kuajak kau melihat kebun salak milikku yang baru saja berbuah. Tidak begitu luas. Tapi kujamin kau akan letih setelah mengelilinginya.”
Aku menyetujuinya. Masalah menginap itu. Juga masalah melihat kebun salak milik Lukman. Tapi aku katakan, aku tidak bisa berlama-lama. Besok sore aku harus sudah kembali ke Jakarta. Kulihat Lukman mengangguk juga meski wajahnya menunjukkan rasa yang lain.
Sementara Indri? Dia hanya mematung. Sesekali mata kami saling beradu pandang. Sebentar saja. Debur itu menghantam lagi didadaku. Sama hebatnya ketika pertama kali kakiku sampai disini, di desa ini, beberapa saat yang lalu.
***
Malam masih belia. Langit sedang cerah. Ada sesuatu yang lain disini. Aku merasakannya. Sangat. Kedamaian yang belum pernah aku jumpai dimanapun. Tenang. Jakarta tak pernah menyuguhkan keadaan seperti ini.
Aku kembali berbincang dangan Lukman. Indri sedang mengajari putranya menyelesaikan pekerjaan rumah oleh-oleh dari sekolah tadi siang. Suaranya lamat-lamat kudengar. Begitu sabar.
Sepanjang sore tadi Lukman membawaku berkeliling kebun salak miliknya. Ada beberapa pohon yang buahnya sudah siap dipetik. Aku senang melihatnya. Kebun salak itu dan tentu saja Lukman. Ia berhasil sekarang. Banyak hal yang dia punya. Keluarga yang menyenangkan, beberapa buku karyanya sudah terbit, juga kebun salak yang sudah mulai berbuah. Aku semakin kagum.
“Besok sore aku akan mengantarmu ke bandara. Sekarang kau istirahatlah. Tentu kau letih sekali hari ini.”
Lukman berlalu. Aku mengatakan kalau aku masih ingin menikmati malam di sini. Lukman membiarkan aku sendirian.
Aku memanfaatkan keadaan ini sebaik mungkin. Menyelami ketenangan yang mengagumkan. Kubiarkan kekagumanku menyeruak menari. Aku ingin seperti ini hingga larut malam nanti.
“Aku masih menemukanmu, sama seperti dulu, Lang.” Indri, tiba-tiba saja dia berdiri diambang pintu.
Aku tersentak. Benar-benar terkejut. “Maksudmu?”
“Jawab dengan jujur, Lang, kemana pergimu ketika Lukman mulai masuk diantara kisah yang sudah kita jalin? Kau pengecut, Lang.” suara Indri begitu lirih namun sangat tajam menusuk. Begitu juga tatapannya.
Aku menunduk. Untuk saat ini, hanya itu yang bisa aku lakukan.
“Apa kau masih mencintaiku, Lang?”
Pertanyaan ini bukan saja tajam menusuk, tapi hampir membunuhku. Aku harus mengatakan apa? Kembali ke masa lalu, mengingat semua kesalahan, lantas berusaha memperbaikinya saat ini, tentu bukan perkara yang gampang.
Sepi kembali berkuasa.
“Lang, jawab.”
Aku membenarkan letak dudukku sejenak, “In, sudahlah. Semua sudah lewat. Aku tak perlu menjawabnya. Kurasa kau lebih paham dan tau mengapa hingga sekarang aku belum juga berkeluarga.”
“Sesederhana itu kah?”
“Ini sangat rumit, In. Sama seperti waktu itu. Aku juga Lukman sama-sama suka padamu. Sekarang semuanya sudah jelas bukan?”
“Lantas, foto itu?”
Kali ini aku yang tersenyum. “Tidurlah, In. Malam telah larut.” Aku menggeliat, merentangkan tangan. “Benar apa kata Lukman tadi siang. Mengelilingi kebun salak kalian bisa membuat tubuhku letih. Selamat malam, In.”
***
Disinilah aku sekarang, dikamarku sendiri yang dibungkus dengan gemuruh dan gerah kota Jakarta. Paraksari sudahpun kutinggalkan sore tadi. Kebun salak, jadah tempe, juga Indri. Dadaku masih bergetar sekalipun hanya kelebat bayangan Indri yang datang. Seperti saat ini.
Kuingat, aku masih menyimpan foto gadis yang kusebut sebagai ‘Indriana’ dihadapan Lukman dulu. Bahkan dihadapan Indriana yang sesungguhnya. Aku merasa begitu bodoh.
Kukeluarkan foto ‘Indriana’ dari dalam dompet. Kupandangi lekat-lekat. Gadis ini memang cantik. Aku tersenyum. Kulirik jam dinding yang tergantung persis di atas bingkai foto Indri. Indriana yang sesungguhnya. Pukul dua puluh satu lebih empat belas menit. Belum terlalu larut. Kuputuskan untuk menelpon ‘Indriana’, gadisku ini.
“Ada apa, Mas?” suara Indriana, di seberang sana.
“Mama udah tidur?”
“Belom. Mau ngomong sama mama?”
Aku menggeleng. Ah, gobloknya aku. “Gak. Mas cuma mau bilang sama kamu kalo kemaren Mas ke Jogja. Nginep di rumah Indri. Di rumah Lukman maksud Mas.”
“Oya? Mbak Indri apa kabar? Pasti dia kaget banget pas dia tau kalo Mas Elang yang datang.”
Aku tertawa. Lantas kisah yang terjadi kemarin meluncur begitu saja. Mengalir dengan leluasa. Sayang, aku belum sempat bilang ke Lukman dan Indriana kalau aku punya seorang adik perempuan yang namanya Indriana juga.
22 Maret 2011
Makasih buat De' Lin yang udah kasi info tentang Desa Paraksari. Deskripsinya bagus banget. Makasih ya...